Hembusan angin tak henti-hentinya mempermainkan ujung-ujung jilbabku. Aku yang sejak tadi duduk menemani Rani di joglo rektorat kampus sibuk membenahi jilbabku yang mulai acak-acakan. Sementara Rani, seolah-olah tak merasa terganggu sedikitpun dengan hembusan angin yang semakin lama semakin nakal kurasakan. Bahkan, tak cukup untuk membuatnya berpaling dari kegelisahan dan kegundahan yang ia rasakan sekarang. Tepatnya, malam ini.
“Jujur Fath, aku tidak bisa menolaknya. Dia terlalu baik pada keluargaku. Dan andai saja kau tahu, dialah yang selama ini membiayaiku hingga aku duduk di bangku kuliah seperti saat ini”, ucap Rani tiba-tiba dan mengejutkanku.
“Yah…, sejak kepergian bapak saat aku masih dikandungan, seolah-olah ibulah yang menjadi tulang punggung keluargaku. Beliaulah wanita perkasa yang menyekolahkanku hingga SMU walau dengan biaya yang tersendat-sendat. Tetapi, toh akhirnya aku bisa me-rampung-kannya juga”.
“Hingga, pada suatu saat seorang laki-laki asing datang ke rumah sederhanaku, yang mungkin lebih cocok disebut sebagai sebuah gubug daripada rumah karena ketidaklayakannya”.
“Dia berbincang-bincang lama sekali dengan ibu, lamat-lamat kudengar bahwa selama ini kurang lebih tiga tahunan ini dialah yang selalu mengirimkan uang untuk biaya sekolahku lewat wesel pos. Hal itu semata-mata ia lakukan karena ia sadar telah berdosa dengan meninggalkan ibu dan menelantarkanku. Selanjutnya, hanya samar kudengar permohonan maafnya berulang-ulang pada ibu untuk kembali menebus dosa dan kesalahannya di masa lalu.”
Aku berusaha mencerna kata-katanya, bukan berarti aku ‘lola’ (loading lambat) lho. Tapi, memang kadang-kadang Rani suka bicara hal-hal yang menurutku sangat tiba-tiba dan filosofis. Jadi, kupikir tidak salah kalau aku butuh waktu untuk mencerna kata-katanya. Kubenahi lagi letak kacamata minus empatku yang mulai melorot, kemudian segera aku konsentrasi kembali untuk mendengarkan ceritanya. Jangan sampai ketahuan kalau ternyata aku tadi masih berpikir. Cepat-cepat aku pun mengomentari ceritanya.
“Jadi, maksudmu sebenarnya apa?, Dia yang kamu maksud itu siapa?,Mbok ya, kalau cerita itu yang jelas tho! Jadi, biar nanti aku bisa memberimu solusi yang jitu. Okay?”, dengan logat Jawa yang medhok khas Ngawi aku mencoba untuk bersikap seolah-olah aku mengerti apa yang ia katakan baru saja.
“Hhaah!, Masya Alloh!, jadi dari tadi yang kamu dengarkan itu apa sih? Koq masih tanya-tanya lagi? Sebel!”,sambil manyun dia berusaha untuk sabar menghadapiku.
Dasar Rani, dia selalu saja mengalah padaku. Terhitung tiga tahun sudah aku berteman dengannya. Atau, lebih tepatnya bersahabat. Aku sama-sama bertemu ketika menjadi mahasiswa baru di kampus biru ini. Ada sesuatu yang aneh ketika aku bertemu dengannya. Aku seperti pernah bertemu sebelumnya, tetapi entah dimana. Mungkin saja de javu, pikirku saat itu.
Hari-hariku bersamanya benar-benar bermakna. Bagaimana tidak, ia mengajariku banyak hal terutama satu hal yang tak pernah kulupakan hingga detik ini, dia mengenalkanku tentang indahnya Islam yang sebelumnya tak pernah kurasakan pun dari keluargaku sendiri.
Walau terhitung sudah 19 tahun aku memeluk Islam, tetapi sebenarnya aku selama ini memaknainya hanya sebatas ritual-ritual keagamaan saja. Tak pantas rasanya aku protes kepada kedua orang tuaku, kenapa mereka tidak sejak dulu mengenalkanku pada Islam yang sebenarnya. Yah, mungkin lebih tepatnya tak adil bagi mereka, toh selama ini aku tak pernah complain. Asal uang jajan lancar, yang lain bisa dinomorduakan. Begitulah prisipku dulu.
Kalaupun aku harus protes, seharusnya lebih tepatnya kutujukan kepada Papa. Beliaulah yang harus bertanggung jawab dengan ke-Islamanku selama ini. Dia meninggalkanku dan Mama hanya untuk menebus dosanya di masa lalu. Tiba-tiba saja dia menjadi tak peduli kepada keluargaku, lebih tepatnya aku dan Mama. Kebetulan kita hanya bertiga; Papa, Mama, dan Aku, anaknya –Fathia Azmi Salsabila- seorang calon sarjana pendidikan yang masih saja sibuk mencari jati diri.
Papa yang sebelumnya sering meninggalkan sholat dan bahkan cuek dengan agama, tiba-tiba saja menjadi rajin beribadah, sholat lima waktu berjamaah selalu ia lakukan di masjid dekat rumah. Bahkan, sehari pun tak pernah ia lewatkan. Aku yang belum paham saat itu, menilai Papa terlalu berlebihan, bahkan sekedar perhatian untuk Mama pun jadi berkurang.
“Papa kejam!, Papa tak berperasaan!”, teriakku saat Papa benar-benar meninggalkan keluargaku tiga tahun lalu.
Papa, entah di mana engkau sekarang. Walau seperti apa adanya dirimu saat ini, aku tetap anakmu, aku merindukanmu, Papa.
Kuseka air mataku yang tiba-tiba saja menetes dalam alam bawah sadarku.
Sebaliknya, saat ini aku benar-benar bersyukur. Allah telah mempertemukanku dengan seorang Rani yang sabar, lembut, dan penyayang. Sampai detik ini, seolah-olah aku lupa akan keberadaan Papa. Padahal sebenarnya di lubuk hatiku yang paling dalam aku ingin menemukamu kembali. Hingga jika saatnya tiba nanti, aku bermimpi, kau akan memeluk dan menciumiku seperti dulu lagi.
Ah…!kerinduan ini begitu memuncak, hingga tak sadar Rani mengagetkanku dengan tepukan lembutnya di pundakku.
“Eh, lagi nglamun ya? Maaf deh kalau aku harus memaksamu untuk mendengarkan ceritaku”, ucap Rani mengagetkanku.
“Terus, gimana nih! mau ku lanjutkan lagi nggak?atau, lebih baik kita pulang saja yah? kurasa, udara malam terlalu buruk buat kesehatanmu!”, ucap Rani selalu saja bernada menasehatiku, dia begitu peduli dengan kesehatanku.
Waktu menunjukkan pukul sembilan malam, aku dan Rani berjalan menyusuri koridor kampus diselimuti hawa dingin khas Malang serta pekatnya malam. Walaupun kulihat banyak bintang, tetapi bintang tetap angkuh pada malam walau hanya untuk sekedar memberikan secercah cahayanya. Sementara malam, ia begitu jual mahal untuk tidak meminta cahayanya pada bintang. Mungkin seperti itulah perumpamaan kami berdua, sebenarnya aku dan Rani sama-sama membutuhkan. Akan tetapi, aku dan Rani sama-sama sombong dan egois walau hanya sekedar berterus terang tentang mendung yang selama inienyelimuti hati kami.
***
Hari berganti hari, aku dan Rani sama-sama sibuk konsentrasi pada penelitian sebagai bahan menyusun skripsi. Belum lagi amanah-amanahku baik di organisasi internal maupun eksternal kampus yang semakin bertambah peran, sehingga membuatku bertahan dan enggan untuk segera meninggalkannya. Sampai-sampai perbincangan saat di joglo rektorat kemarin sempat terlupakan.
Memang, setelah malam itu aku dan Rani sama-sama berkomitmen untuk membuktikannya kepada kedua orang tua kita. Kami akan lulus kuliah tepat waktu dengan hasil memuaskan. Konsekuensinya, kami jadi jarang bertemu, paling cuma sebatas telepon-teleponan. Itupun tidak lama, hanya untuk sekedar melepas kerinduan.
Hari itu, tiba-tiba Rani menelepon dan mengajakku janjian untuk bertemu di kampus. Katanya, ada hal penting yang harus ia ceritakan. Akupun mengiyakan. Setelah selesai bimbingan, aku langsung menuju kantin mbak Yam tempat kami biasa janjian. Selain tempat curhat paling aman, di sini jarang ada wartawan yang mau meng-ekspose obrolan kita, walau hanya sekedar candaan.
Rani membuka pembicaraan dengan menanyakan kabar dan keadaanku selama ini. Aku pun membalasnya dengan hal serupa. Namun, tiba-tiba saja dari pipinya yang putih kemerahan buliran-buliran bening itu jatuh. Ia menangis rupanya, pikirku. Kubiarkan ia menumpahkan segalanya, sampai pada satu hal yang mengejutkanku ia mengatakan bahwa laki-laki asing yang pernah ia ceritakan saat di joglo rektorat malam itu tak lain adalah ayah kandungnya. Masih dengan terisak, Rani mencoba untuk menceritakan kejadian sebenarnya.
Ia memulai dengan kisah ibunya yang seorang kembang desa, tiba-tiba dipinang oleh laki-laki kota yang saat itu sedang melaksanakan progam kuliah kerja nyata (KKN) dari kampusnya. Tanpa menelusuri asal-usul si pemuda, karena keluguan dan kepolosannya ia menerima begitu saja ajakan dari sang pemuda untuk menikah walaupun usianya saat itu masih terbilang sangat muda. Bisa dibayangkan, di sebuah desa pada saat itu masih belum ada kantor catatan sipil seperti sekarang. Sehingga akhirnya mereka menikah di bawah tangan hingga kemudian setelah beberapa bulan menikah, ibu Rani mengandung. Akan tetapi, pemuda yang menikahinya tersebut tak kunjung kembali setelah berpamitan pulang ke kota dengan tujuan memberitahu keluarganya. Ternyata, sebenarnya di kota oleh orang tuanya ia telah dijodohkan dengan seorang wanita kerabat jauh ayahnya yang berasal dari Ngawi. Dan, pemuda itupun tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya pasrah dan terpaksa menuruti kemauan orang tuanya.
Sementara aku, hanya terdiam dan terpaku menatapnya. Walaupun sebenarnya dalam hati aku berkata, sebenarnya aku sama, juga merindukan kehadiran seorang ayah. Yah…, ayah. Beruntung sekali Rani, ia telah menemukannya meski harus menunggu lama.
Tak lama, setelah selesai bercerita ia pun menyeka air matanya. Aku melihat ada haru dan bahagia di sana, di bening matanya. Dalam kelembutan matanya, ternyata benar dugaanku selama ini bahwa tersimpan kesedihan yang saat ini sudah tak kutemukan.
***
Beberapa hari yang lalu aku berkesempatan silaturahim ke rumah Rani, tepatnya di daerah Malang Selatan tak jauh dari terminal Gadang hanya sekitar satu jam ditempuh dengan naik bus jurusan Malang-Dampit. Tepatnya dimana, aku juga sudah lupa. Tetapi kenangan itu sebenarnya tak pernah kulupakan, pun hingga saat ini.
Aku sempat bertemu dengan ibunya, walau belum terlalu tua tetapi sudah terlihat sangat renta. Guratan-guratan di pipinya sudah terlihat melepuh dan jatuh, tidak sekencang pipi wanita seusianya. Pandangan matanya juga sudah meredup, seolah-olah beliau begitu memaknai hidup. Berjuang sendirian untuk dapat menghidupi diri dan anaknya. Tanpa seorang suami di sisinya, ia rasakan pahit getirnya hidup. Pun tanpa bantuan dari sanak keluarga, karena bagi kebanyakan orang desa mempunyai anak tanpa suami adalah aib. Aku hanya berkata dalam hati, barangkali memang karena kerasnya hidup hingga menjadikannya tak sempat lagi merawat dirinya. Berbeda dengan Mama, Mama yang terlihat selalu peduli dengan jadwal ke salon langgananya. Apalagi sejak kepergian Papa, ia seperti tidak mempunyai pegangan hidup. Ia mencari kesibukan di luar rumah, berbagai usaha jual beli rumah dan tanah ia terjuni walau beresiko, arisan tiap hari, sampai lupa kalau ternyata ia masih punya aku, anaknya.
Aku benar-benar jadi tamu istimewa. Di jamu dengan berbagai jajanan pasar sederhana yang sebelumnya aku tak pernah menemuinya di rumah. Teh hangat, menambah hangatnya pertemuan kami. Dia hanya sedikit memberiku dan Rani wejangan-wejangan agar lebih dewasa dan bijaksana dalam memaknai hidup.
Sayangnya, aku tidak bertemu dengan ayahnya. Tetapi, tak apalah lain kali pasti aku akan bertemu. Mungkin nanti kalau aku main-main lagi ke rumahnya, batinku dalam hati. Aku pun kemudian berpamitan pulang. Rani mengantarkanku hanya sampai jalan besar tempat pemberhentian bus. Tak lama kemudian, sebelum melepasku naik bus ia pun berpamitan pulang.
Akan tetapi, setelah kepergian Rani tiba-tiba saja aku reflek ingin melihat jam hanya sekedar memastikan sekarang sudah jam berapa, sehingga aku bisa mengira-ngira jam berapa nanti aku akan sampai di rumah. Ternyata, aku baru teringat kalau tadi setelah selesai wudhu untuk menjalankan sholat dhuhur aku lupa mengambilnya lagi. Seingatku, jam tangan itu masih ada di kamar mandi rumah Rani. Bergegas aku kembali menyusuri jalan-jalan dengan sawah di kanan kirinya untuk menuju rumah Rani dengan segera.
Sesampainya di pintu rumahnya, aku mendapati Rani sedang mencium punggung tangan seorang laki-laki yang sangat tidak asing lagi bagiku. Kuhentikan langkahku untuk masuk ke dalam rumah itu. Kemudian, kuusap-usap mataku dan segera kupastikan bahwa aku tidak sedang berada di alam mimpi. Yah, laki-laki itu tak lain adalah ayahku. Ayah yang meninggalkanku tepat tiga tahun lalu.
Seketika itu, aku tersadar. Kemudian aku berlari meninggalkan rumah Rani dengan tumpahan air mataku yang tak henti-hentinya menetes. Entahlah, mungkin sebaiknya Rani tidak mengetahuinya. Biarlah aku tetap angkuh seperti bintang. Walaupun angkuh, tetapi sebenarnya itu kulakukan demi menjaga keindahan malam . Malam akan kehilangan keindahannya jika ia terlalu terang karena cahaya bintang.
SELESAI
*ini adalah cerpen pertama saya yang saya tulis hanya dalam waktu satu setengah jam untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis cerita dan naskah drama




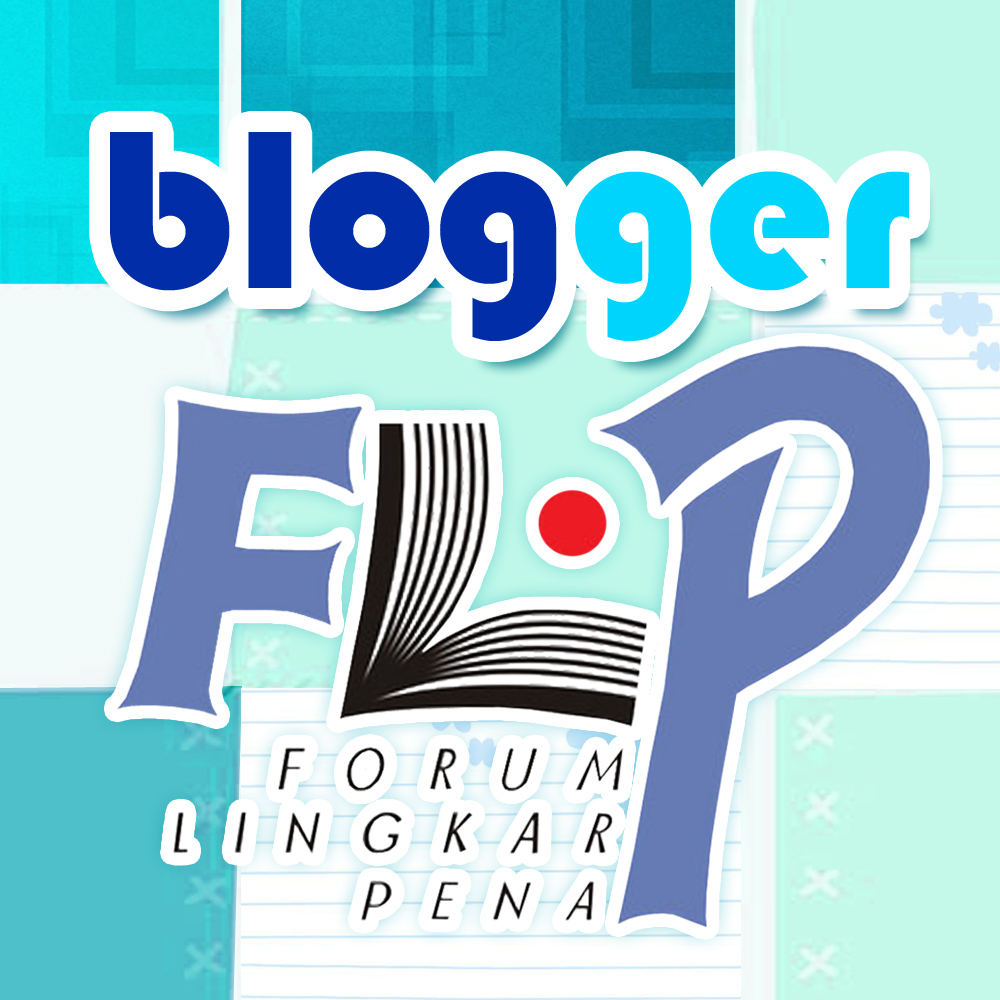




0 komentar:
Posting Komentar