Tak Seperkasa Lautan
Barisan lumut memenuhi bola mataku yang kian meredup. Pagi ini Malang kembali menunjukkan keperkasaannya, seolah dialah satu-satunya kota pemilik dingin, walaupun sebenarnya tak lestari, sekarang.
Kotek ayam membuatku mengurungkan niat untuk kembali merapatkan selimut kumal kesayangannku. Seolah mengerti bahasa ayam yang ingin segera disuapi, aku pun bangun dari peraduan. Aroma dedak kembali memenuhi rongga hidungku yang tak begitu mancung. Sama seperti kemarin. Mungkin akan selalu terjadi besok, lusa, atau kapanpun aku tak pernah tahu rutinitas ini segera berakhir.
Tunai sudah tugasku pagi ini sebelum aku berangkat ke sebuah sekolah dasar Islam terpadu di daerah Malang Selatan untuk mengabdikan sedikit ilmu yang telah kuperoleh di kampus dulu. Walau sampai saat ini pun aku belum juga mendapatkan gelar sarjanaku, tetapi semua orang sudah mengakuiku sebagai seorang guru. Tepatnya seorang guru SD.
Kembali kuberjalan menyusuri desa dengan khas Jawa Timuran. Ibu-ibu kampung pun tak segan menyapaku walau hanya sekedar abang-abang lambe mempersilakan singgah di rumahnya sebentar. Tak apalah pikirku kemudian.
Sudah terhitung hampir tiga bulan lebih aku tinggal di desa ini bersama suamiku tercinta. Suami yang mempersuntingku genap sebulan setelah aku diterima mengajar di sebuah sekolah dasar Islam terpadu di daerah Malang Selatan. Bagaimana tidak? Kami memang satu sekolah, tetapi jujur tidak ada ketertarikan sebelumnya. Kami berproses menuju gerbang pernikahan melalui murobbi.
Diiiiiiiiiiiin! Diiiiiiiiiiin!, lamunanku buyar aku dikejutkan suara klakson supir angkot langganan.
***
“Aku capek, Kak. Jujur, aku hari ini capek banget, Kak”. aku kembali mengeluh, Hari ini aku memang capek. Bersandar di bahunya seolah bisa mengurangi beban
berat di pundak.
“Kau kira aku nggak capek, Din?”, dengan nada berat dan tampak kesal ia membalas keluhanku yang terkesan manja dan minta diperhatikan. Dingin. Ia membiarkan kepalaku tergolek lemah di bahunya yang kokoh.
Memang. Siapa yang tak kenal Azzam Putra Hanif, seorang pentolan aktivis da’wah. Di kampus, semua birokrat tak ada yang tak mengenalnya, para akhwat juga selalu punya dan menyimpan nomor HPnya. Di kampung, siapa yang tak tahu sepak terjangnya. Di struktur da’wah, terkenal jadi rebutan saat itu.
Sementara aku? Siapa loh! Aku hanya seorang perempuan, perempuan biasa. Aktivitasku dalam da’wah juga tidak terlalu menonjol. Waktu di kampuspun aku tak seberapa mengenalnya. Di sekolah, tak banyak yang ku tahu dari sosoknya yang terkesan angkuh dan garang saat itu. Tak berubah masih sama, seperti dulu. Dingin.
“Kakak mau dipijitin?”, tanyaku walau sebenarnya aku sedang berusaha memecah kebekuan diantara kami berdua.
“Nggak usah deh!”, tanpa sedikitpun menoleh ke arahku. Ia pun kemudian bergegas berdiri, menyambar acer kesayangannya. Biasanya, aku menyebut benda itu istri keduanya. Bahkan mungkin rasa sayangnya lebih besar dibandingkan kepadaku, istrinya.
“Dunia benar-benar gila!”.
“Hari ini saham PT Lapindo dilepas lagi”.
“Gila!, Kontraktor mana lagi yang berani membeli?”
“Sepertinya aku tak yakin bisa terjual cepat. Tak mungkin”.
“Kau tahu? Advokasi yang kulakukan bersama teman-temanku membawa dampak . Setidaknya hal ini direspon oleh para wakil rakyat yang duduk di sana.”
Yah, begitulah kesehariannya. Ada sebuah tanya di benakku yang lara. Akankah harus seperti ini setiap hari? Aku menggaruk-garuk kepalaku yang tak gatal, berusaha menemukan jawaban. Walau akhirnya tak kunjung kutemukan jawabannya. Pias. Tubuh ini kembali lunglai. Aku pun menerawang teringat wejangan ibu sebulan setelah penikahanku.
“Laki-laki itu dimana-mana tugasnya jadi pemimpin, jadi tidak ada alasan karena da’wah dia tidak menafkahimu”.
“Nafkah batin saja, itu ndak cukup nduk”,kamu juga butuh uang untuk beli bedak.”
‘Tapi, buk...”, seperti ada sesuatu di tenggorokanku berat, tercecat. Seolah tak satu pun untaian kata sanggup ku keluarkan dari sana.
“Mboten...., ibu mboten usah kuatir”.
Kususun kekuatan, berusaha sekuat tenaga untuk menyunggingkan sedikit senyum, walaupun sebenarnya kutahu itu sebuah senyum penuh kepasrahan. Dengan sedikit keterpaksaan, akhirnya senyum itu pun mengembang dari bibirku yang kelu.
“Kalau hanya untuk beli bedak saja, anakmu ini masih sanggup kok bu”.
“Siapa dulu ibunya...”, aku pun terkekeh.
“Ooalah nduk..., nduk..., kalau memang itu pilihanmu ya sudah. Orang tua ini kan cuma mengkhawatirkan. Yah, paling-paling bapak ibumu ini cuma bisa mendoakan. Lebih dari itu? ya, jangan harap.
***
Kukayuh sepeda miniku dalam keremangan malam yang hanya diterangi kunang-kunang. Hembusan angin sedari tadi usil seolah ingin mengajakku bergurau. Tapi sayang, kehendak ini tak menyambut, debaran dada seolah mengalahkan bisikan angin yang berusaha agar aku terusik. Tapi tidak.
Sama. Seperti malam-malam sebelumnya, sepulang dari pengajian rutin mingguan. Malam, kegelapan, kunang-kunang, angin yang nakal, sampai rembulan seolah menjadi kawan diperjalananku.
Rembulan. Aku ingin menjadi rembulan. Rembulan senantiasa memberi cahaya
dalam kegelapan, tersenyum walau sebenarnya penuh jelaga di dunia. Seperti tak ada masa tuk sekedar rehat tak mengeluarkan sinarnya.
“Mas Hanif?...., dimana kau sekarang? Tak perlu kau mengingatku. Batin ini sudah cukup tenang tatkala kutahu niatanmu hanya untuk meraih ridhoNya.
Hari ini aku masih bisa menjadi rembulan, kok. Batinku kemudian. Menghadirkan senyuman simpul yang menggemaskan bagi orang yang sedang memperhatikan. Mungkin.
Titik-titik (panggilan kesayangan untuk ayam-ayam yang kami pelihara) kita sudah bertelur semua. Alhamdulillah, hasilnya lumayan untuk tambahan ongkos angkot tiap pagi ke sekolah. Tapi, Mas..., hari ini aku tak bisa bertemu wajah polos murid-muridku yang selalu ingin tahu. Kau tahu kenapa? Aku terpeleset dari atap rumah. Sakit sih!, tapi tidak parah kok. Aku kan rembulan masih bisa tersenyum walau sesakit apapun.
***
Dinda, tak seharusnya kau melakukan itu semua. Ku tahu kau adalah rembulan. Kau ingin menjadi rembulan. Selalu tersenyum pada malam, tak kau hiraukan lara dalam batinmu.
Malam, dengan keangkuhannya seolah ia adalah pemilik kegelapan. Tak punya inisiatif tuk hanya hadirkan keindahan dengan sinar. Karena bagimu pekat adalah keindahan malam. Paradoks sekali, rembulan dan malam.
Beberapa hari yang lalu ketika ku hanya punya waktu beberapa jam untuk memenuhi undangan pertemuan para kativis da’wah di Malang, kutemukan mata beningmu, senyum tipis dan lesung pipit dari wajah mungilmu yang datar. Ku hampiri kau yang terlihat sayu, kau pun kemudian berceloteh menceritakan kejadian itu. Memang, tak seharusnya itu kau lakukan. Membetulkan atap rumah yang bocor. Kau sangat lucu dan polos bagiku.
Dinda, kau tahu aku adalah lautan bagimu, ketenangan selalu kau dapatkan dari getaran ombakku, biruku juga selalu menawan untuk kau kenang.
“Bukankah begitu, Din?”
Sama. Seperti saat kutinggalkan, kau hanya tersenyum dan sedikit berucap,
“Karena aku tak seperkasa Lautan, Kak”
Selesai.
Malang, 14 September 2006
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Total Tayangan Blog
Menu
Archive Blog
-
▼
2018
(67)
-
▼
Februari
(14)
- Cincin Mahar
- Forum Lingkar Pena (FLP): Cerita Segala Rasa
- Cermin Kaca Retak (1)
- Belajar Bersyukur Ala Kids Zaman Now
- Kopi Susu Cinta untuk Spensalu
- Dokter Babe: Solusi Konsultasi Kesehatan Sekali 'K...
- Menjadi Mentor yang Mengasyikkan, Why Not?
- Teaching with Heart
- Nyanyian Tentang Hujan
- Selang Air
- Merindu Ber-Temu Kunci
- Tips Membersihkan Kerang Darah
- Wanita yang Dirindu Surga
- Tak Seperkasa Lautan
-
▼
Februari
(14)

Blog Archive
-
2018
(67)
- Oktober (1)
- September (3)
- Juli (1)
- April (1)
-
Februari
(14)
- Cincin Mahar
- Forum Lingkar Pena (FLP): Cerita Segala Rasa
- Cermin Kaca Retak (1)
- Belajar Bersyukur Ala Kids Zaman Now
- Kopi Susu Cinta untuk Spensalu
- Dokter Babe: Solusi Konsultasi Kesehatan Sekali 'K...
- Menjadi Mentor yang Mengasyikkan, Why Not?
- Teaching with Heart
- Nyanyian Tentang Hujan
- Selang Air
- Merindu Ber-Temu Kunci
- Tips Membersihkan Kerang Darah
- Wanita yang Dirindu Surga
- Tak Seperkasa Lautan
- Januari (47)
Jejak Karya

Cinta Semanis Kopi Sepahit Susu adalah buku single pertama saya, yang terbit pada tanggal 25 April 2017 tahun lalu. Buku ini diterbitkan oleh QIBLA (imprint BIP Gramedia). Buku ini adalah buku inspiratif dari pengalaman pribadi dan sehari-hari penulis yang dikemas dengan bahasa ringan tapi syarat hikmah. Ramuan susu dan kopi cinta dari hati penulis ini menambah poin plus buku ini sangat layak dibaca bahkan dimiliki.


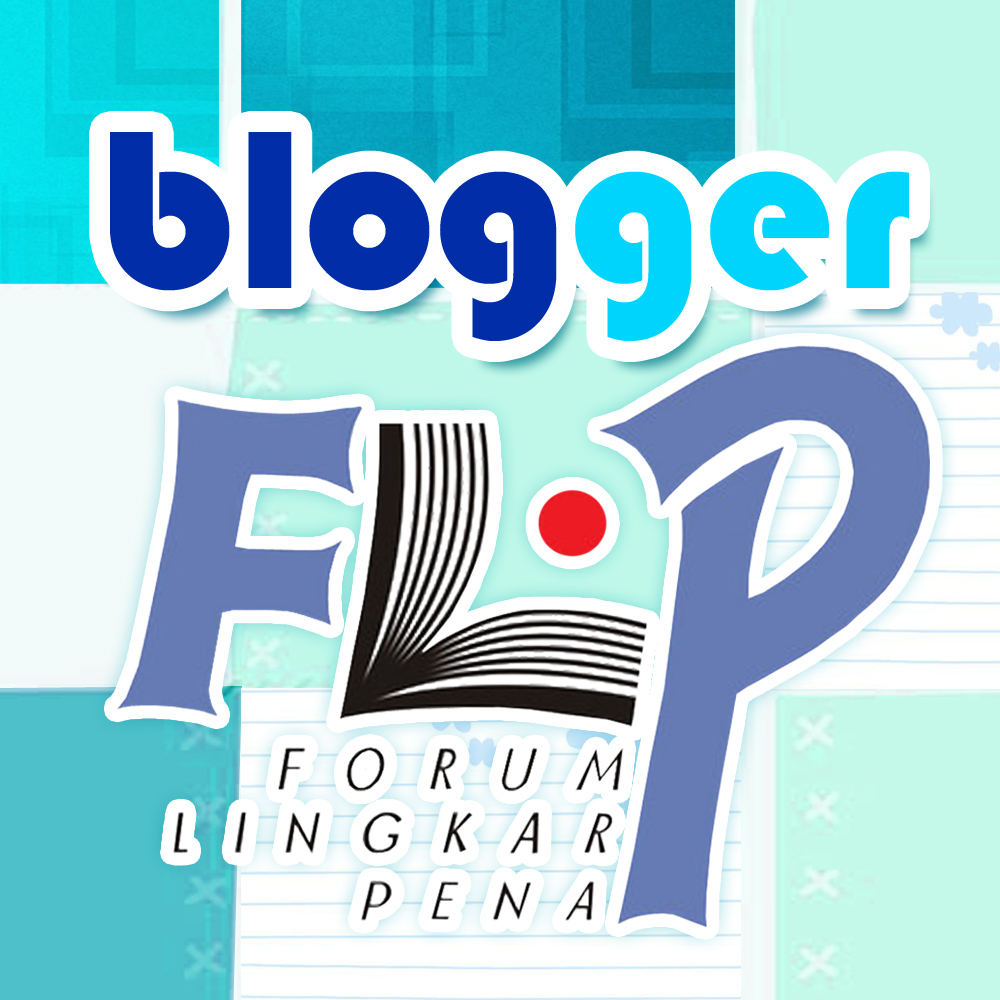




0 komentar:
Posting Komentar